PERTEMUAN pertama kali dengannya, guru saya, saya tak mungkin lupa, adalah bada Isya di tahun 1992, di Singawinata, depan ruangan TU. Saya bersama Roy—Ahmad Royani, teman sekelas di 1.2, genjreng-genjreng main gitar tak karuan. Ia datang dari arah kantor, memakai sarung dan berkaos oblong putih. Tangannya disampirkan ke punggungnya, “Jangan berisik di sini. Ini bukan tempat main. Kamu siapa?”
Saya melongo. Saya berpikir ketika itu, ini pasti guru. Saya segera menyebut nama saya. Namun sesaat kemudian, seorang senior kelas 2, entah siapa namanya, yang baru belajar motor bebek, menabrak gerbang sekolah. Saya, Roy, dan ia kemudian malah jadi sibuk menolong anak kelas 2 itu. Saya ingat, besoknya diperingati Isra Miraj di sekolah kami.
BACA JUGA: Kamu nggak tau aja…
Satu tahun kemudian, ia masuk ke kelas 2 saya. Kelas bahasa. Ia mengajar Sejarah. Tapi ia mengenalkan sastra sedikit demi sedikit. Itu pertama kalinya kami diajar oleh dia, guru kami. Pertama kali pula dalam kelasnya, saya membaca puisi Sutardji Calzoum Bahri berjudul “Pot”—saya kurang begitu ingat apa hubungannya pelajaran Sejarah dan membaca puisi. Saya tak pernah melupakan apa yang dia katakan soal puisi itu. Hari-hari berikutnya di kelas 2, ia pertama kali mengajarkan teater dan sastra. Dan kami, kelas 2, saat itu merasa gemuk dengan hal-hal seperti itu.
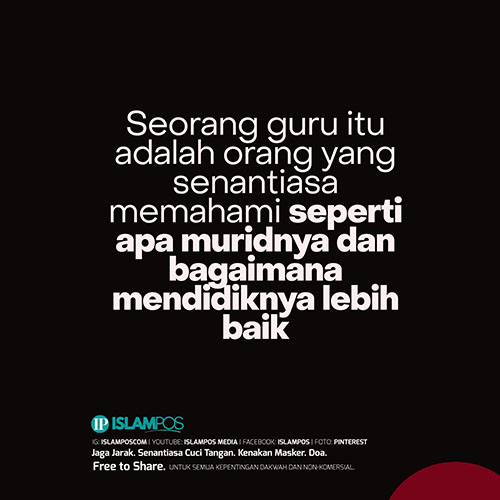
Pertama kalinya, di peringatan bulan bahasa di tahun 1993, ia, guru kami, menyanyi depan kantor. Saya masih ingat, ia menyanyi “Sanggupkah Aku” dari Andy Liani. Kami sebagian para muridnya di kelas Bahasa, berdiri memperhatikannya. Ia bernyanyi sambil duduk di sebuah kursi panjang. Ia, guru kami, begitu muda.
Pertama kalinya di tahun 1994, ia mengajak saya ke Bandung. Buat saya, itu nyaris kunjungan pertama kali keluar kota. Ia, guru saya itu, membawa saya ke Uninus. Saya yang tadinya mau masuk pesantren karena sadar dari keluarga miskin dan tak mungkin lanjut studi ke perguruan tinggi, tiba-tiba tersontak, “Pak, saya akan kuliah. Di jurusan Inggris,” ujar saya malu-malu padanya, mungkin tanpa suara. Ia tersenyum, “Kalau kamu ke ITB atau Unpad, gedungnya lebih besar daripada Uninus ini…”
Pertama kalinya di tahun 1996, ketika saya menganggur, ia memberikan sebuah majalah berisi pengumuman lomba menulis cerpen tingkat nasional. Ia tidak berbicara apapun, tapi mungkin menyuruh saya untuk ikut. Tiga bulan kemudian, saya jadi juara ketiga lomba menulis cerpen itu. Saya ingat, hadiahnya saya jadikan sebagai uang pangkal masuk kuliah. Dan saya juga ingat, kata istri saya sekarang, ia, guru saya, membacakan cerpen itu di semua kelas yang ia ajar. Ia bangga pada cerpen itu.
BACA JUGA: Kopi 7 Cerita
Kamis malam Jumat, ia pulang. Pulang. Guru kami. Guru saya. Dan tak akan pernah kembali. Jam 23.00 saya di-SMS oleh seorang sahabat di kelas Bahasa, dan segera merapat ke rumahnya. Pukul 02.00 dini hari, jenazahnya diberangkatkan ke Belitung, tanah yang ia cintai dan banggakan. Saya masih terus bisa menahan diri melihat semuanya. Rak-rak buku. Motor yang sempat dititipkan pada saya jika ia mudik lebaran. Putra sulungnya dan anak perempuan keduanya yang jadi sahabat anak perempuan saya. Dan beberapa yang lain lagi.

Tapi saya akhirnya tak kuasa ketika mengecup putrinya berusia 4 tahun. Air mata saya tumpah. Ia pulang di hari yang baik. Dan di bulan yang baik.
Seorang guru saya pernah bilang, “Guru tak pernah mati. Ia selalu hidup dalam hati kita.” Saya menyimpan perkataan itu dalam diri saya. []















