SETIAP daerah, suku, negeri, dan kelompok masyarakat, biasanya memiliki adat istiadat yang telah berjalan secara turun temurun. Baik adat tersebut dalam bentuk pakaian, atau perilaku, atau ucapan, atau kegiatan, atau rumah, atau permainan dan yang lainnya.

Adat secara bahasa dari kata “al-‘aud” atau “al-mu’awadah” yang artinya berulang-ulang. Adapun secara istilah, adat adalah: “Sebuah ungkapan untuk apa-apa yang telah tetap di dalam jiwa berupa perkara-perkara yang telah terjadi berulang-ualng serta diterima di sisi tabi’at yang lurus.”
Adat, hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sepanjang tidak termasuk dalam perkara yang dilarang oleh syari’at, maka hal ini merupakan perkara yang selayaknya untuk dijaga dan dilestarikan.
BACA JUGA: Mengenal 4 Disiplin Keilmuan Tradisional Islam
Jangan sampai menyelisihi adat setempat, lebih-lebih mengubahnya. Karena biasanya, hal itu akan menjadi sebab terjadinya kegaduhan, pertikaian, dan fitnah di tengah masyarakat.
Dan perkara seperti ini, terlarang di dalam syari’at Islam. Karena agama ini dibangun di atas prinsip: “Memperbanyak kemaslahatan dan meminimalisir kerusakan”.
Jika dalam perkara sunah saja kita dianjurkan untuk menunda mengamalkannya apabila berpotensi akan menyebabkan terjadinya fitnah atau kegadudah di tengah masyarakat, apalagi masalah adat yang status hukumnya hanya mubah (boleh).
Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu ‘anha, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Tidakkah kamu tahu wahai Aisyah! Bahwa kaummu ketika membangun Ka’bah mengurangi/tidak menyempurnakan sesuai dengan qawaid Ibrahim.”
Aisyah berkata: “Wahai Rasulullah! apakah anda tidak punya keinginan untuk mengembalikannya sesuai qaidah
Ibrahim?” Beliau menjawab:

Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah berkata:
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ إلَّا فِي الْحَرَامِ فَإِنَّ الرَّسُولَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – تَرَكَ الْكَعْبَةَ وَقَالَ «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ الْجَاهِلِيَّةَ»
“Ibnu Aqil berkata di dalam “Al-Funun”: Tidak seyogyanya untuk keluar dari berbagai adat manusia, kecuali dalam perkara yang haram. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggalkan (untuk mengembalikan) Ka’bah (kepada bentuknya yang sesuai dengan yang dibangun Nabi Ibrahim) seraya berkata: “Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kejahiliyahan (sungguh aku akan melakukannya)”. (Al-Adabusy Syar’iyyah : 2/43).
Imam Asy-Syafi’i (w. 204 H) rahimahullah berkata:
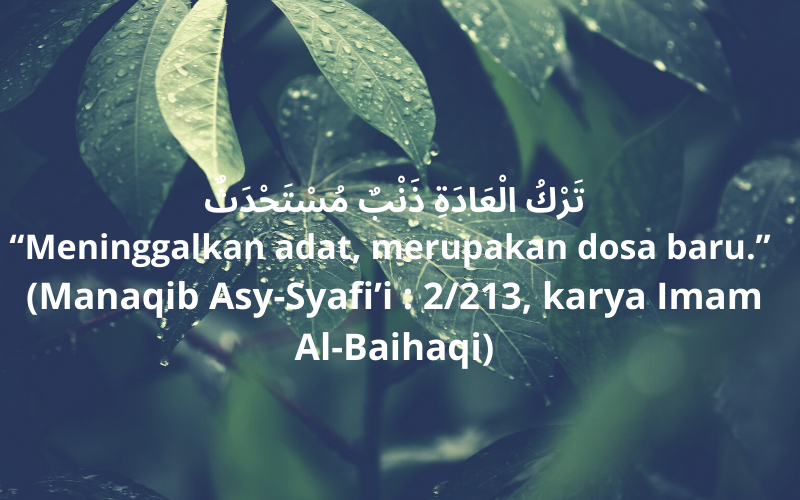
Umar bin Al-Khathab radhiallahu ‘anhu meninggalkan untuk menulis ayat rajam, karena khawatir manusia di zaman itu akan menuduhnya menambah Al-Qur’an.
BACA JUGA: Dari Tradisi hingga Ibadah, Inilah Serba-Serbi Seputar Ramadhan
Imam Ahmad pernah mengamalkan shalat dua rekaat qabliyyah Maghrib sebagaimana dalam “Al-Fushul”. Lalu beliau meninggalkannya setelah itu, karena manusia kala itu tidak mengerti masalah ini sehingga mereka mengingkarinya.
Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Adapun jika suatu tradisi jelas-jelas bertentangan dengan syari’at, maka tidak boleh untuk kita ikuti.
Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha menyelaraskan diri dengan adat/tradisi di daerah kita tinggal, selama ia tidak ada pelanggaran terhadap syariat. Baik dalam hal berpakaian, amaliah, dan yang lainnya.
Termasuk dalam hal ini adalah berbagai masalah yang hukumnya masih diperselisihkan ulama (khilafiyyah). Menyesuaikan diri dengan tradisi/adat setempat, merupakan perkara yang dituntut di dalam syari’at kita.
Intinya, jangan nganeh-anehi (tampil beda). Demikian, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Walhamdulillah Rabbil ‘alamin. []
Facebook: Abdullah Al Jirani















