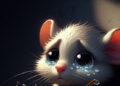SUATU kali aku dalam perjalanan pulang kerja, istriku menelpon. Padahal aku sudah akan tidur di bus. Aku bekerja di luar kota dan hampir setiap hari pulang-pergi memakai bus antarkota.
“Ya, ada apa?” tanyaku.
“Aku tadi sangat terharu,” ujarnya terbata-bata, “aku hampir menangis…”
Aku tiba-tiba mendapat firasat yang tidak enak. “Ya, ada apa gerangan?”
“Anak kita, si nomor satu…”
Aku segera mengingat wajah anakku nomor satu yang perempuan. Ia saat ini duduk di kelas 1 SD, baru masuk hanya beberapa bulan lalu. “Kenapa dengan dia?”
“Aku tadi merasa sangat haru dan sekaligus bangga….”
“Kamu berbelit-belit. Sakitkah dia?”
Tampaknya dia menggelengkan kepala. Aku merasakannya. “Tidak. Tadi di sekolahnya, ada pemotretan untuk buku raportnya…”
Aku menarik nafas lega. Setikaknya bukan sesuatu yang buruk yang akan kudengar dari mulut istriku selanjutnya, aku sudah cukup yakin. “Terus….?”
“Ia menceritakan kepadaku bahwa tadi ketika pemotretan akan dimulai, ibu guru kelasnya berkata bahwa semua murid perempuan harus membuka jilbabnya ketika difoto. Supaya tidak repot, begitu katanya…”
“Lantas?”
Istriku menarik nafas sejenak. “Lihatlah, aku masih tidak bisa menahan tangis karena haru. Kemudian ia berkata kepada gurunya… ‘Ibu guru, bolehkah aku tetap memakai jilbabku saja kalau difoto?’”
Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mendengarkan dengan saksama.
Istriku melanjutkan. “Kemudian, ibu gurunya berkata, ‘Ya , silakan kalau kamu mau….’ Ia menjadi satu-satunya anak perempuan di kelasnya yang difoto dengan jilbabnya, begitu menurut penuturannya tadi. Aku langsung terharu. Aku langsung mengatakan kepadanya, ‘Nak, kamu boleh tidak mendapatkan nilai seratus dalam setiap pelajaran kamu. Namun apa yang sudah kamu lakukan sekarang, itu membuat Bunda sudah bangga akan kamu.’ Aku langsung memeluk dia. Sambil menangis.”
Aku mulai paham. “Ya…” ujarku tapi tidak bisa mengatakan yang lainnya.
“Kemudian aku bertanya kepadanya, ‘Kenapa kamu tidak mau difoto tanpa jilbab kamu?’. Ia menjawab, ‘Aku malu, Bunda.’”
Telepon kemudian di tutup. Aku melihat keluar jendela bus yang melaju cepat. Aku mengingat kembali telepon istriku. Aku mengingat anakku yang nomor satu, si tujuh tahun itu. Aku tersenyum dan bergetar. Ia sudah beranjak menyebalkan dalam banyak hal. Tapi aku tidak pernah berpikir ia bisa seperti itu; menolak difoto di ruangan publik tanpa jilbabnya.
Sesampainya di rumah, ia masih belum tidur. Ia masih mengerjakan PR-nya. Aku tersenyum kepadanya, dan mengecupnya.
Setelah aku mandi, makan dan salat, ia dan adiknya laki-laki memintaku mendongeng Si Mimin, sebuah tokoh asal Meksiko yang komiknya menjadi bacaan favoritku sewaktu aku kecil. []