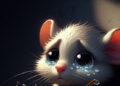AMANI Ballour (32), dokter wanita asal Suriah, baru-baru ini dianugerahi penghargaan Dewan Eropa atas dedikasinya menyelamatkan ribuan nyawa korban konflik di Suriah. Selama enam tahun, hijaber yang kini tinggal di Turki itu menjalankan sebuah rumah sakit bawah tanah. Di sana dia melakukan misi kemanusiaan, memberikan pertolongan kepada ribuan warga sipil yang terluka akibat perang di wilayahnya.
Perjalanan Ballour telah ditampilkan dalam sebuah film dokumenter National Geographic, berjudul ‘The Cave’. Film ini dinominasikan sebagai peraih Oscar dalam kategori Fitur Dokumenter. The Cave disutradarai oleh Feras Fayyad dan diproduksi oleh Kirstine Barfod dan Sigrid Dyekjær. Pada 2018, Fayyad dinominasikan untuk penghargaan akademi untuk Last Men di Aleppo. The Cave menceritakan kisah mengerikan perjuangan Ballour untuk memberikan penyembuhan dan kenyamanan di tengah-tengah perang di rumah sakit bawah tanah.
Dikutip dari Nasional Geographic, berikut ini profil dan kisah Ballour yang menginspirasi dunia:
Sebagai putri bungsu dalam keluarga yang terdiri dari tiga anak perempuan dan dua anak laki-laki, Ballour mengatakan bahwa sejak kecil ia bercita-cita “untuk melakukan sesuatu yang berbeda” daripada sekedar menjadi ibu rumah tangga seperti kakak perempuannya yang menikah pada usia remaja dan awal 20-an.
Hatinya berfokus pada teknik mesin, hingga ia mendaftar di Universitas Damaskus. Tetapi tekanan dan pandangan masyarakat serta penentangan ayahnya terhadap rencananya, mendorong hijaber itu untuk beralih ke dunia kedokteran, suatu disiplin yang katanya dianggap “karier yang lebih tepat untuk seorang wanita, tetapi sebagai dokter anak atau dokter kandungan”.
Ballour memilih menjadi dokter anak dan mengabaikan banyak penentang yang mengejek dengan mengatakan kepadanya bahwa “‘begitu Anda menikah, gantungkan gelar Anda di dapur.”
“Saya mendengar ungkapan ini berkali-kali,” kata Ballour.
Pada 2011, ketika gelombang protes damai Arab mencapai Suriah, Ballour adalah mahasiswa kedokteran tahun kelima, setahun lagi lulus. Protes dengan cepat menelan Ghouta Timur. Ballour berbaris dalam sebuah demonstrasi tetapi tidak memberi tahu keluarganya karena yakin bahwa orangtuanya akan sejuta persen menentangnya [karena] mereka sangat takut sesuatu akan terjadi pada putrinya. Pada protes lain, dia menangkap cuplikan singkat video tetapi terlalu takut untuk menyebarkannya.
“Saya takut ditahan,” katanya.
Namun, pengalaman itu menggembirakan bagi Ballour.
“Rasanya seperti saya menghirup kebebasan, itu luar biasa. Itu sangat memberdayakan hanya untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap apa yang terjadi di negara ini yang telah diperintah selama beberapa dekade oleh satu rezim,” kata Ballour.
BACA JUGA: Selamatkan Ribuan Nyawa, Dokter di Suriah Raih Penghargaan dari Dewan Eropa
Pada saat itu, Bashar Assad dan, sebelum dia, ayahnya Hafez — telah memerintah Suriah dengan tangan besi selama lebih dari empat dekade. Ballour ingat bagaimana sebagai seorang anak dia tahu bahwa “dilarang untuk berbicara tentang hal-hal tertentu, untuk menyebutkan nama presiden, Hafez al-Assad, dengan cara apa pun kecuali untuk memujinya [karena] tembok-tembok itu memiliki telinga.”
“Saya hanya mendengar bisikan pembantaian Hama 1982, ketika pasukan Hafez al-Assad menewaskan ribuan orang, pemberontak dan warga sipil, dalam pemberontakan Islam yang berumur pendek. Orang tua saya tidak memberi tahu kami tentang pembantaian Hama, dan mereka dipaksa tutup mulut,” katanya.
Ketika Bashar al-Assad menggantikan ayahnya pada tahun 2000, Ballour bertanya-tanya mengapa warga Suriah tidak dapat memilih seorang pemimpin dengan nama keluarga yang berbeda.
“Ketika saya bertanya tentang hal itu, saya diberitahu untuk diam, bahwa seseorang mungkin mendengar kami,” katanya, “Itu sangat menakutkan.”
Ketika negara Suriah dengan keras menindak gerakan protes, memukuli demonstran dengan tongkat seperti cambuk dan menembakkan gas air mata dan peluru tajam ke kerumunan, Ballour ditarik ke dalam situasi yang memburuk, tetapi bukan sebagai pengunjuk rasa. Pada tahun-tahun awal revolusi Suriah, pasukan keamanan secara rutin memburu para demonstran yang terluka di rumah sakit. Mereka yang mencari perawatan medis berisiko ditahan —menghilang ke jaringan penjara bawah tanah rezim— atau lebih buruk lagi, terbunuh di tempat.
Klinik lapangan rahasia diam-diam bermunculan di rumah dan masjid dan tempat-tempat lain. Ballour ingat dipanggil dari rumah oleh tetangga untuk merawat pasien pertamanya, yang terluka dalam sebuah protes. Itu pada akhir 2012 dan dia baru saja lulus.
“Dia adalah seorang anak yang ditembak di kepala. Apa yang bisa saya lakukan untuknya? Dia sudah mati,” katanya, “Dia berumur sekitar sebelas tahun.”
Pekerjaan pertama Ballour, sebagai sukarelawan tanpa bayaran, merawat yang terluka di sebuah rumah sakit lapangan yang didirikan di sebuah bangunan yang sebagian dibangun oleh rezim yang dijadwalkan menjadi sebuah rumah sakit. Dia adalah salah satu dari dua dokter penuh waktu yang bekerja di sana. Yang lainnya adalah pendiri klinik, Salim Namour.
Namour ingat pertemuan pertamanya dengan Ballour setelah dia lulus.
“Dia memperkenalkan dirinya dan menawarkan bantuan,” kenang Namour. “Banyak dokter berpengalaman melarikan diri ke tempat yang aman tetapi di sini ada lulusan muda yang tetap tinggal untuk membantu.”
Pada saat itu, fasilitas tersebut terdiri dari ruang operasi dan ruang gawat darurat di ruang bawah tanah. Ini akan segera berkembang menjadi jaringan tempat penampungan bawah tanah dan dikenal oleh penduduk setempat sebagai Gua. Bangsal termasuk pediatri dan penyakit dalam ditambahkan. Lebih banyak dokter, perawat, dan sukarelawan bergabung dalam upaya ini. Rumah sakit mengandalkan mesin dan peralatan yang diambil dari rumah sakit yang rusak di dekat garis depan, dan menyelundupkan pasokan medis yang dibayar oleh LSM internasional dan Suriah di diaspora.
Ballour bukan ahli bedah trauma, tetapi ketika korban datang, bahkan dokter hewan dan dokter mata merawat yang terluka. Dia harus belajar dengan cepat, bukan hanya obat darurat, tetapi juga menghadapi kengerian perang yang biadab. Korban massal pertama yang dilihatnya adalah mayat hangus. Bahkan bertahun-tahun kemudian, dia dapat dengan jelas mengingat “bau orang terbakar tanpa bisa dikenali dan beberapa dari mereka masih hidup.
“Itu adalah hal yang paling mengejutkan yang pernah saya lihat pada saat itu, saya masih belum memiliki pengalaman, saya adalah lulusan baru. Saya sangat terkejut saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya. Tetapi kemudian saya melihat banyak pembantaian, begitu banyak korban, dan saya mulai bekerja,” tutur Ballour.
BACA JUGA: Razan Al Najjar, Malaikat Pelindung yang Gugur di Tangan Sniper Israel
Pada 21 Agustus 2013, Ballour dan rekan-rekannya yang berdedikasi menghadapi kengerian baru: senjata kimia. Serangan Sarin di Ghouta Timur menewaskan ratusan. Ballour ingat bergegas ke rumah sakit di tengah malam, memilih jalan melewati orang-orang, mati dan hidup, tergeletak di lantai untuk mencapai ruang pasokan untuk mulai merawat pasien.
“Kami tidak tahu persis apa itu, hanya saja orang-orang mati lemas. Semua orang adalah kasus darurat. Seorang pasien yang mati lemas tidak bisa menunggu, dan mereka semua mati lemas. Kami menyelamatkan siapa yang kami selamatkan dan yang tidak kami dapatkan pada waktunya mati. Kami tidak bisa mengelola,” kata Ballour.
Tahun berikutnya, Namour membentuk dewan medis lokal dari 12 dokter yang tersisa yang melayani populasi sekitar 400.000 orang yang terperangkap di Ghouta Timur. Dewan itu termasuk dua dokter gigi dan seorang dokter mata. Tidak semua anggota dewan bekerja di Gua, tetapi bersama-sama mereka memutuskan untuk memilih administrator Gua untuk masa enam bulan, yang kemudian diperluas menjadi satu tahun. Menjelang akhir 2015, Ballour memutuskan berdiri untuk posisi itu.
“Saya tidak mengerti mengapa saya tidak bisa menjadi administrator terutama jika itu hanya karena jenis kelamin saya. Saya seorang dokter dan mereka (dua administrator pria sebelumnya) adalah dokter. Saya berada di rumah sakit sejak hari pertama, saya tahu apa yang dibutuhkan, saya punya ide untuk mengembangkannya, saya punya rencana,” kata dia.
Ayah dan saudara laki-lakinya menyarankan untuk tidak melakukannya, mengingat Ballour sudah menghabiskan seluruh hari dan malamnya di Gua.
“Ayah saya mengkhawatirkan saya, tetapi saya tidak bisa pulang,” kata Ballour. “Tidak ada cukup dokter. Dia mengatakan kepada saya bahwa orang tidak akan menerima saya, bahwa saya akan menghadapi banyak masalah. Keesokan harinya saya mencalonkan diri dan terpilih sebagai administrator rumah sakit. ”
Ballour mengambil alih posisinya pada awal 2016, beberapa bulan setelah serangan udara bergejolak dengan kedatangan Angkatan Udara Rusia di langit di atas Ghouta Timur. Serangan balik dari beberapa pasien dan kerabat mereka cepat dan dapat diprediksi.
“Apa yang saya dengar dari banyak pria adalah, ‘Apa? Apakah kita kehabisan pria di negara ini untuk menunjuk seorang wanita? ‘Seorang wanita. Mereka tidak mengatakan dokter wanita, tetapi seorang wanita,” kenang Ballour.
Sebagai seorang wanita yang mungil dan lembut dengan wajah yang mengingatkan pada potret Renaisans, Ballour bersaing dengan buadaya patriarki yang konservatif —terutama pasien dan kerabat mereka— yang menantang otoritasnya untuk menjalankan fasilitas medis masa perang.
“Dulu aku sangat vokal menjawab,” katanya, merujuk pada pria yang akan memberitahunya bahwa tempatnya ada di rumah.
“Saya tidak akan tinggal diam karena ketika Anda benar, Anda benar.… Beberapa pria akan mengatakan itu berbahaya, daerah itu dikepung, itu adalah pekerjaan yang sulit sehingga pria harus melakukannya. Mengapa? Seorang wanita juga bisa melakukannya, dan saya melakukannya,” lanjut dia.
Dia didukung penuh dalam upayanya oleh staf rumah sakit, termasuk Namour.
“Saya tidak bisa menerima pembicaraan [patriarkal] ini,” kata dokter senior itu, “Saya akan memberi tahu para pria: Dia ada di sini bersama kami, bekerja siang dan malam kapan pun kami membutuhkannya sementara beberapa dokter pria yang kita semua tahu melarikan diri ke daerah yang dikontrol rezim untuk bekerja dengan aman. Yang mana yang Anda sukai? Ini bukan tentang gender, ini tentang tindakan dan kemampuan, dan Dr. Amani membuat banyak perubahan positif ke rumah sakit.”
Ballour memperluas Gua, memperdalam bunker dan menggali terowongan ke dua klinik medis kecil di kota —dan ke pemakaman.
“Kami perlu menguburkan yang mati tetapi terlalu berbahaya untuk berada di atas tanah,” katanya, “Kami tidak bisa bergerak di atas tanah.”
Ketika pengepungan semakin ketat dan pesawat-pesawat tempur berteriak di atas kepala, ada peluang untuk pergi melalui terowongan, tetapi Ballour tidak mengambilnya.
“Bagaimana saya bisa pergi?” Katanya, “Mengapa saya belajar kedokteran dan fokus pada anak-anak jika tidak membantu orang? Untuk berada di sana ketika mereka membutuhkan saya, bukan untuk pergi ketika saya ingin.”
Jumlah korban setiap hari naik ke tiga digit. Rumah sakit itu berulang kali menjadi sasaran serangan udara yang menembus jauh ke dalam Gua, menghancurkan bangsal, menewaskan tiga personel dan melukai yang lainnya. Pada satu kesempatan, Ballour baru saja melangkah keluar dari bangsal ke koridor ketika roket jatuh di belakangnya.
“Aku tidak bisa mendengar apa pun atau melihat apa pun. Koridor itu penuh debu tebal yang menggantung di udara,” kenang Ballour.
Ketika itu dibersihkan, dia menemukan rekan-rekannya yang sudah mati dalam kondisi tubuh hancur berkeping-keping.
Ambulans dipukuli dan penyelamat terbunuh ketika mereka mengambil yang terluka. Dorongan terakhir Assad ke Ghouta Timur pada Februari 2018 termasuk serangan klorin.
“Bau klorin luar biasa,” ingat Ballour, “Saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan seperti apa itu, bagaimana kita hidup, tetapi saya ingin agar orang-orang mengerti mengapa kami pergi. Orang-orang lelah dan lapar. Banyak yang menyerah, termasuk para pejuang yang akan menjatuhkan senjata mereka dan pergi ke arah tentara rezim. … Tentara mendekati kita. Mereka tidak jauh, kami harus melarikan diri. Kami takut mereka akan membunuh kami jika mereka mencapai kami. ”
Komisi Penyelidikan PBB tentang Suriah kemudian melaporkan bahwa pasukan Suriah dan sekutu melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama pengepungan dan merebut kembali Ghouta Timur. Metode perang Assad di Ghouta adalah “biadab dan abad pertengahan,” kata laporan PBB itu, termasuk “pengepungan yang paling lama berjalan dalam sejarah modern, yang berlangsung lebih dari lima tahun.”
Pada 18 Maret 2018, Amani Ballour dan timnya mengevakuasi korban yang terluka dan meninggalkan Gua, tetapi tidak sebelum dokter melewati setiap kamar dan mengucapkan selamat jalan.
“Saya memikirkan semua orang yang telah melewati rumah sakit ini. Saya masih kecil ketika bangunan yang akan menjadi rumah sakit dibangun, dan saya kemudian bekerja di dalamnya selama enam tahun. Kami dikepung di sana, diserang di sana, kami menyelamatkan dan kehilangan nyawa di sana. Saya memiliki begitu banyak kenangan di tempat itu, sebagian besar menyakitkan tetapi kami juga bersenang-senang. Sangat, sangat menyakitkan bagi saya untuk meninggalkan rumah sakit.”
Dia berjalan pergi dengan pakaian apa pun di punggungnya, meninggalkan mantel putih yang dia kenakan sejak dia masih mahasiswa kedokteran.
“Itu berlumuran darah sehingga saya tidak bisa membawanya,” katanya. “Mantel itu sangat istimewa bagiku.”
Ballour dan beberapa anggota keluarga dan kolega termasuk Namour awalnya melarikan diri ke Zamalka di dekatnya, sebuah pinggiran Damaskus, tetapi ada juga penembakan di sana. Sepuluh hari kemudian, Ballour kembali bergerak, kali ini ke provinsi Idlib di Suriah barat laut yang berbatasan dengan Turki, benteng pemberontak terakhir di negara itu. Dia belum pernah ke Idlib sebelumnya. Dia pindah dari kota ke kota di provinsi itu, tetapi tidak ada yang lolos dari pesawat tempur. Dia menawarkan diri untuk membantu dokter anak di rumah sakit lapangan desa tetapi tidak bisa tinggal lebih dari beberapa jam di fasilitas tersebut.
“Ketika saya melihat anak-anak di Idlib saya ingat anak-anak saya dan apa yang terjadi pada mereka. Saya tidak bisa melihatnya lagi. Saya sangat lelah secara psikologis dan fisik.”
Dia juga bosan mendengar beberapa orang di Idlib, sebagian besar pejuang Islam, menyalahkan dia dan yang lainnya di Ghouta Timur untuk apa yang mereka sebut “menyerah” kepada rezim. Setelah tiga bulan di Idlib, dia melarikan diri ke Gaziantep, Turki pada Juni 2018. Dia menikah dengan seorang aktivis dari Daraa yang telah berkomunikasi dengannya ketika dia berada di Ghouta tetapi tidak pernah bertemu sebelumnya.
Sekarang, dia aman, tetapi dia tidak bahagia. Matahari musim dingin mengalir melalui jendela apartemennya. Dia tidak lagi di bawah tanah, tetapi dia hidup dengan kepahitan menjadi seorang pengungsi di negeri asing, berjuang dengan beban, dan kenangan mereka yang tidak selamat, terutama anak-anak.
“Mereka ada di depan mataku,” katanya, “Ada anak-anak yang tidak bisa saya lupakan, tidak mungkin melupakan mereka. Ada anak-anak yang akan saya rawat di bangsal anak-anak (untuk asma dan penyakit lainnya) dan kemudian saya akan melihat mereka ketika mereka terluka. Rasanya seperti merawat keluarga. Saya tidak bisa melihat mata mereka ketika saya bekerja pada mereka. Kadang-kadang saya jatuh, saya hancur.”
Dia masih memiliki mimpi buruk dan setiap suara keras mengingatkannya pada sebuah pesawat perang. Selama badai, katanya, jika suaminya tidak ada di rumah, dia memanggilnya untuk meyakinkannya bahwa suara itu bukan serangan udara. Dia mengulang percakapan dengan beberapa pasien mudanya, seperti Mahmoud yang berusia lima tahun yang kehilangan tangan karena pecahan peluru, dan dengan air mata bertanya kepada Ballour mengapa dia mengamputasinya.
“Apa yang bisa saya katakan kepadanya ketika dia menanyakan itu kepada saya? Saya banyak menangis hari itu. Dan kemudian ada anak laki-laki yang kehilangan lengannya di bahu. Aku masih bisa mendengarnya berteriak kepadaku, memintaku membantunya.”
Di Suriah, kata Ballour, dia merasa berguna, seperti dia membuat perbedaan. Sementara di Turki, tempat yanga mana baginya kini, Ballour merasa seperti tidak ada apa-apanya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan menjadi sukarelawan bersama kelompok perempuan Suriah dan belajar bahasa Inggris dengan harapan berimigrasi ke Kanada, tetapi beberapa proposalnya telah ditolak.
“Sejujurnya, kata pengungsi adalah label yang sulit dipakai. Saya mencintai negara saya, rumah saya, hidup saya di Suriah, ingatan saya akan hal itu, tetapi mengapa kami menjadi pengungsi? Orang-orang harus bertanya apa yang ada di balik kata ‘pengungsi’ dan mengapa kami melarikan diri. Saya seorang pengungsi karena saya melarikan diri dari penindasan dan bahaya. Saya tidak ingin pergi. Saya lebih suka tinggal di Ghouta, terlepas dari segalanya. Kami dikepung dan dibombardir dan kami bertahan selama enam tahun, kami tidak ingin pergi. Itu adalah momen yang sangat, sangat sulit. … Saya berharap bahwa orang-orang yang hanya memandang kami sebagai pengungsi bertanya apa yang kami hindari dan mengapa kami pergi. Itu kata yang menyakitkan tetapi saya tidak punya pilihan. Saya tidak percaya saya punya pilihan,” ungkapnya.
Ballour bermaksud untuk melanjutkan praktik kedokteran, tetapi bukan sebagai dokter anak. Sebagai gantinya, dia berencana untuk beralih ke radiologi, karena dia berkata, “Saya tidak bisa melihat pasien secara psikologis lagi, terutama anak-anak.”
Ini adalah sentimen yang dipahami Namour.
“Saya adalah seorang ahli bedah yang menghabiskan hidupnya di ruang operasi, tetapi setelah pengalaman pahit yang kami alami, setelah tidak berperikemanusiaan dan penderitaan yang kami saksikan di Ghouta, saya tidak tahan melihat darah atau berada di ruang operasi,” katanya, ” Meskipun bagiku operasi adalah teknik, seperti pelukis yang mengerjakan potret. Kami selamat dari hari-hari yang sangat sulit.”
BACA JUGA: Hujan Deras, Pengungsi Suriah Hidup di ‘Rawa-Rawa’
Ballour menemukan cara lain untuk membantu masyarakat. Dia terlibat dalam penggalangan dana, bernama Al Amal (Hope), untuk mendukung perempuan dan pekerja medis di zona konflik. Dia adalah advokat yang kuat untuk membantu jutaan warga Suriah yang terlantar yang tinggal di kota-kota tenda di Suriah dan jutaan lainnya yang telah menjadi pengungsi di luar perbatasannya.
Perang Suriah telah tergelincir dari halaman berita tetapi Ballour bertekad untuk memberi tahu orang-orang tentang kekejaman yang dia saksikan dalam perang selama hampir sembilan tahun yang tidak pernah berakhir.
“Saya tidak ingin bercerita untuk membuat orang menangis dan marah, saya ingin mereka membantu,” katanya, “Masih banyak orang yang membutuhkan bantuan.”
Dan kemudian, ada masalah keadilan. Anak yang orang tuanya terlalu takut untuk bercerita tentang pembantaian Hama sekarang menjadi dokter wanita yang bertekad untuk menyebarluaskan kesaksiannya tentang serangan kimia di Ghouta Timur.
“Saya harus menyampaikan kesaksian ini kepada organisasi yang suatu hari nanti semoga bisa membuat rezim bertanggung jawab atas kejahatan ini,” katanya, “Saya melihatnya. Itu terjadi.”
“Satu hal yang membantu saya adalah mengetahui bahwa kami berada di kanan, di sisi kanan sejarah karena kami menentang ketidakadilan,” lanjutnya.
“Hati nurani saya jelas. Saya memiliki kewajiban terhadap orang-orang dan saya memenuhinya sebaik mungkin dengan sarana yang saya miliki. Tetapi kadang-kadang saya menyesal pergi dan menyalahkan diri sendiri, tetapi kemudian saya berkata saya tidak punya pilihan. Ini adalah kebenaran dari perasaan yang saling bertentangan dalam diri saya. Saya mencoba membantu, dan itu membantu saya, bahwa saya adalah seorang kemanusiaan,” pungkas dokter wanita pemberani dari Suriah itu. []
SUMBER: NATIONAL GEOGRAPHIC