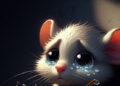TAK ada yang bisa memilih, kita akan lahir di rahim siapa, berkulit apa, dan dimana. Saya, 7 bersaudara:
6 Muslim, 1 Nasrani.
5 orang menikah dengan ‘pribumi’.
Ayah masuk Islam di usia 73 tahun, setahun sebelum meninggal.
Ibu masuk Islam tahun lalu, di usia 79 tahun.
Ayah dan Ibu suku Tionghoa atau Anda sering menyebut dengan ‘Cina’.
Saya dan keluarga tak pernah teriak, “Si Kafir itu…” kepada siapapun. Kenapa?
Mau nyimak cerita Ayah saya?
Ayah saya adalah sosok nasionalis dan idealis tulen yang saya kenal. Cita-citanya menjadi ABRI tak terpenuhi, karena orang tua tak mengijinkan. Kakak pertama saya melanjutkan cita-cita itu sebagai ABRI. Kakak ketiga gagal menjadi ABRI, karena mata sedikit minus. Jika ditanya, “Papah gak pengin jalan-jalan keluar negeri?” Jawabnya, “Ngapain? Indonesia aja bagus, gak habis keliling Indonesia”.
18 tahun kerja di bank swasta, dengan prestasi terakhir menaikkan revenue perusahaan 20 kali lipat dalam 5 tahun menjabat, ‘dipaksa’ mengundurkan diri karena membela seorang karyawan baru ‘pribumi’, yang akan digeser oleh titipan direksi (tionghoa) yang rasialis.
Kemudian beliau melanjutkan kerja di usia 50 an, sebagai manajer keuangan di suatu perkebunan di Lampung. Percakapan yang paling saya ingat saat berkunjung kesana, “Ya’ (panggilan saya), coba lihat, orang-orang (buruh) itu dibayar dibawah angka kebutuhannya (UMR). Kalau mereka punya anak 3 atau lebih, gak akan cukup untuk hidup, maka mereka akan ‘maling’. Suatu saat, kalau kamu jadi bos, jangan pernah bayar karyawanmu dibawah angka kebutuhannya.”
5 tahun bekerja sebagai manajer keuangan, membuat ayah saya dikeluarkan, karena membongkar sindikat koruptor yang melibatkan adik pemilik perusahaan. Saat malam terakhir di Lampung, saya mendampingi dan mendengar ta’mir (pengurus) masjid setempat berkata, “Kami sangat kehilangan Pak Untung (ayah saya). Selama Pak Untung disini, ibadah kami, Bapak permudah. Pak Untung sudah seperti orang tua kami.”, air mata saya pun berlinang. Saat itu ayah saya belum memiliki agama, masih Kong Hu Cu (tradisi).
Di usia 55 tahun lebih, ayah melanjutkan bekerja di Purbalingga. Memilih tinggal di rumah penduduk dan mengembalikan fasilitas mobil sedan. Saya pun bertanya, “Kenapa papah balikin mobil itu? Kan bisa dipakai buat transportasi?”. Beliau menjawab, “Gak ahh, malu. Lha wong mereka (buruh) masih dibayar dibawah UMR, koq papah orang baru, udah pakai mobil mewah. Gimana omongan papah akan didengar mereka?”.
Akankah Anda mengatakan “Cina Kafir” kepada ayah saya?
Sekarang kisah saya.
Di usia 7 tahun (1980), sejak pindah ke rumah yang ketiga, kami tinggal di lokasi yang berdekatan dengan kampung di kota Semarang. Sungguh kaget, saat keluar rumah, anak kampung setempat berteriak, “Cino..!!”, dan langsung mengejar kemudian memukuli saya bertubi-tubi. Bosan melarikan diri terus, saya mulai melawan. Mau gak mau belajar berkelahi. Saat SD, kami sekeluarga disekolahkan di SD Katholik, alasan ayah saya, karena disiplinnya bagus.
Namun ayah saya ingin anak-anaknya berbaur, maka saat SMP, kami semua masuk ke SMP negeri, dimana saat itu hanya 2 orang ‘keturunan’ satu angkatan. Kami tak pernah merasa sebagai seorang ‘keturunan’. Ayah kami mendidik kami anti rasialis. Hal itu dibuktikan, ayah saya mengasuh seorang suku Bali, bernama I Gusti Made Gede, kuliah dan tinggal bersama kami selama 8 tahun.
Sungguh kaget, saat kawan-kawan di SMP berteriak, “Cino..!”. Dan saya pun balas berteriak, “Cino matamuuu..!”. Perkelahian pun sering terjadi.
Sejarah masuk Islam
Karena di sekolah negeri, pelajaran ‘default’ agama adalah Islam, kakak pertama saya mempelajari dan tertarik untuk memeluk Islam saat kelas 2 SMP. Kami, adiknya, satu-persatu masuk Islam saat masuk SMP, kecuali kakak perempuan saya. Tentu saja ayah dan ibu saya belum Islam saat itu.
Lulus kuliah, saya merantau ke Batam dan berjumpa dengan istri saya, yang saat itu beragama nasrani. Kenapa istri saya mau mengikuti saya masuk Islam? Inilah perkataannya, “Aku dulu (saat kuliah di Jakarta) sama sekali antipati dengan orang Islam, karena orang-orang Islam yang kukenal, kasar dan rasialis. Waktu ketemu kamu dan kenal kawan-kawanmu (yang muslim), baru aku melihat bahwa Islam itu damai”.
Kakak kami tertua tak pernah meminta kami mengikutinya masuk Islam. Saya pun tertarik masuk Islam di usia 11 tahun, saat SD, karena melihat kakak-kakak saya sholat. Begitu juga, ayah dan ibu saya, tak ada keterpaksaan masuk Islam. Saya meyakini, agama itu adalah akhlaq yang harus ditunjukkan, bukan dalil yang digemborkan. Seandainya, ayah saya mencalonkan menjadi gubernur, saat sebelum masuk Islam, maka saya akan tetap memilih beliau, karena saya tahu, beliau adalah sosok pemimpin yang bijak.
Anda mungkin sudah menebak arah saya kemana. Ya, benar dan mungkin salah. Saya tak memihak Ahok, karena saya tak mengenal beliau dan saya tahu politik terlalu rumit untuk dipahami. Jika pun saya ber KTP Jakarta, maka saya akan memilih Bang Sandiaga Uno, karena beliau adalah mentor saya dan saya ‘lebih’ mengenal beliau. Tidak ada jaminan akan lebih baik dari Ahok.
Poin saya adalah.
Saya pernah kafir dan saya tak suka disebut kafir, juga Cina. Ayah, ibu, kakak, istri saya pernah kafir, dan mereka tak suka disebut kafir, juga Cina. Maka saya tak akan menggunakan kata-kata itu untuk Ahok atau siapapun.
Memaki dan menghujat tak membuat Islam lebih tinggi, justru Anda telah merendahkan Islam dan memecah belah bangsa ini. Kalau Anda yakin Islam “rahmatan lil ‘alamiin”, tunjukkan saja dengan akhlaq, bukan dengan beribu dalil. Hewan dan tumbuhan saja harus kita sayangi, apalagi manusia. Kalau Anda yakin (dan saya yakin), masih banyak pemimpin muslim yang pantas, tunjukkan saja siapa mereka dan apa prestasinya untuk umat.
Bagi Anda suku Tionghoa.
Kita sudah belajar pahitnya jaman rasialis. Jangan Anda mempertahankan rasialis Anda, dengan memilih Ahok karena suku atau agama. Pilihlah pemimpin yang adil, siapapun itu. Terbukti yang membebaskan kita dari rasialisme bukanlah Soeharto, namun seorang Kyai bernama Gusdur.
Bagi yang tak setuju.
Saya tahu perdamaian adalah hal yang mustahil, karena selalu akan ada yang berdalih dengan dalil untuk menyangkal. Benar dan salah itu nisbi di dunia ini, sampai kita tahu kebenaran hakiki di akhirat kelak. Andaikan kelahiran Anda bertukar rahim dengan saya, apakah sikap Anda akan seperti sekarang?
Bukan dalilmu yang membuatku berubah,
tapi kesantunan akhlaqmu yang ingin kutiru.
Kau tarik aku, maka aku melawan.
Kau rangkul aku, maka aku mengikutimu.
foto: keluarga Setiabudi, 1983 []
Sumber: Jaya Setiabudi, http://juraganforum.com/keluargaku-dulu-china-kafir-seperti-kau-sering-teriakkan/#sthash.LurlJp7Q.dpuf