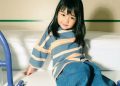Oleh: Eeng Nurhaeni*
nurhaenieeng@gmail.com
DALAM buku yang diterbitkan Fikra Publishing (Jakarta) sejak 2012 lalu, “Revolusi Dunia Pesantren”, Hafis Azhari pernah menjelaskan perbedaan mengenai anak biologis dengan anak ideologis. Belakangan, banyak media luring dan daring menampilkan persoalan yang sehaluan dengannya, dalam headline mereka mengenai perbedaan nasab dan sanad (ilmu). Manakah yang lebih utama dari keduanya?
Nasab keturunan Rasulullah tak bisa dimungkiri sebagai nasab terbaik sepanjang sejarah. Terlebih mereka yang mewarisi ilmu yang mumpuni bagi kemajuan peradaban bangsa dan negara. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa kemuliaan nasab seakan lebih utama, karena ia bersifat “dzati” yang terkait langsung dengan darah dagingnya. Tetapi, sebagian lagi justru berpendapat, bahwa penguasaan dan pengamalan ilmu jauh lebih utama. Untuk itu, seorang anak ideologis lebih mulia dari sekadar menjadi anak biologis semata.
Secara tendensius, Hafis Azhari menyatakan, “Kalau orang itu benar-benar anak biologis dan ideologis sekaligus, mestinya dia seorang yang rendah-hati, tidak ujub dan takabur. Karena bagaimanapun, Rasulullah tak mungkin mewariskan ilmu kecuali yang membawa nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan.”
Tapi dalam suatu iklim yang korup dan tidak adil, diperlukan bahasa ungkapan untuk menegakkan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Terkait dengan ini, Hafis menandaskan bahwa prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan harus melalui koridor dan cara-cara terbaik, bukan melalui dakwah atau ceramah yang memprovokasi massa dengan ujaran-ujaran kebencian. Jadi, prinsip menegakkan keadilannya sudah benar, tapi caranya harus dibenahi dan ditinjau ulang.
BACA JUGA: Apakah Surga dan Neraka Itu Ada?
“Tapi orang itu memang benar-benar memiliki garis keturunan dari Husein dan Fatimah, dan catatan di Rabithah Alawiyah jelas menunjukkan itu,” ujar seseorang pada saat bedah buku Pikiran Orang Indonesia di pesantren Al-Bayan, Rangkasbitung, Banten.
Ada yang mengatakan bahwa kecakapan ilmu dapat hilang dan musnah manakala si ahli ilmu telah menjadi tua dan pikun, atau hilang ingatan. Tetapi, seorang anak biologis tetap paten dan permanen karena darah-dagingnya tetap menyatu dalam dirinya. Banyak ahli-ahli ilmu yang di masa tuanya menjadi lemah tak berdaya, tak mampu mengembangkan pengetahuannya dan berhenti mengajar. Meskipun, fakta sejarah tetap mencatat orang-orang berilmu yang memiliki kualitas dan kapasitas yang membawa kemaslahatan bagi peradaban umat.

Di dalam Alquran ditegaskan bahwa manusia unggul dapat ditakar dari kualitas ketakwaannya. Di sisi lain, akan diangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan dalam beberapa derajat ketimbang yang lainnya. Dengan demikian, kita pun perlu menghargai dan menghormati habib, apakah ia tergolong cerdas atau tidak. Apakah ia termasuk dalam jajaran sunni, syiah maupun wahabi. Kita harus menghormatinya sebagaimana kita harus hormat kepada orang tua kita, apapun ideologinya, serta bagaimanapun sifat yang dimilikinya dalam pandangan kita, baik maupun buruk, bahkan hidup secara islami maupun tradisional (musyrik).
Tetap mereka adalah orang tua kita yang harus diakui dan dihormati tanpa kecuali. Jadi, meskipun kita berseberangan paham dengan mereka, kita harus menyampaikannya dengan cara-cara terbaik. Biarpun kita memandangnya arogan tetapi kita tak boleh bersikap arogan, biarpun mereka bersikap temperamen, kita tak boleh membalas dengan temperamental yang sama. Nabi Ibrahim tidak membalas sikap arogansi bapak dan pemimpinnya (Namrud) melainkan dilampiaskan kepada benda-benda mati, dengan melayangkan kapak kepada berhala-berhala yang berjejer di kuil-kuil istana kerajaan.
Tapi bagaimana jika ada habib yang ajarannya tersesat, atau justru sebaliknya, menyesat-nyesatkan ajaran yang kita anut? Biarkan sajalah, yang penting kita tak perlu ikut-ikutan mengkafirkan mereka. Justru sebaiknya kita muhasabah dan introspeksi diri, sudah sejauh mana kita memiliki kualitas pemikiran yang selama ini kita yakini kebenarannya. Seorang sahabat saya malah berkomentar, “Biarpun ngedangdut model Camelia Malik dan Rhoma Irama, atau bahkan menjadi rocker seperti Ahmad Albar, tetap saja mereka memiliki darah keturunan habib, dan sudah ada pematang sawahnya.”
Seringkali masyarakat awam membutuhkan kejelasan secara eksplisit tentang siapakah yang lebih mulia, nasab atau derajat keilmuan. Maka, saya perlu menceritakan perjalanan hidup seorang cicit Rasulullah, Ali Zainal Abidin ketika melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah.
Dalam buku karya Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny perihal 198 Kisah Haji Wali-wali Allah, diceritakan tentang perjalanan Ali Zainal Abidin yang berjumpa dengan seorang sahabatnya, Thawus bin Kaisan. Kita mengenal Ali Zainal Abidin sebagai figur dan sosok ahli zuhud. Meski dikenal cerdas dan berilmu, tetapi ia memosisikan diri sebagai figur bersahaja, dan tidak menyombongkan diri lantaran garis keturunan nasab yang dimilikinya.
BACA JUGA: Mengeruk Keuntungan dari Konten Kiamat
Suatu ketika, Thawus menyaksikan Ali Zainal Abidin sedang berdiri di bawah bayang-bayang Kakbah. Seperti orang yang tenggelam, Ali menangis seperti ratapan penyesalan seorang yang menderita sakit, lalu berdoa terus menerus seperti sedang terkena masalah yang sangat besar.
Seusai berdoa, Thawus mendekat dan bertanya, “Wahai cicit Rasulullah, aku melihat engkau seperti menderita rasa sakit, padahal engkau memiliki tiga keutamaan yang akan bisa menyelamatkanmu dari rasa takut.”
“Adakah yang membuat aku merasa aman, wahai Thawus?” tanya Ali Zainal Abidin.

Thawus menatapnya dengan seksama, dan tegasnya, “Pertama engkau adalah keturunan Rasulullah, kedua engkau akan mendapatkan syafaat dari kakekmu Muhammad, dan ketiga engkau dipastikan mendapat rahmat Allah…”
Ali mendekat dan berkata di hadapan Thawus dengan nada serius, “Sahabatku, garis keturunanku dengan Rasulullah bukanlah jaminan aku mendapat keamanan, karena Allah berfirman bahwa ketika ditiup sangkakala nanti, maka tak ada lagi pertalian nasab di hari itu (al-Kahfi: 99). Adapun tentang syafaat kakekku, Allah telah berfirman bahwa siapapun takkan sanggup memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi Allah semata (al-Anbiya: 28). Sedangkan, mengenai rahmat Allah yang engkau maksudkan tadi, Allah juga berfirman bahwa rahmat-Nya amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (al-Araf: 56).”
Kembali pada pernyataan Hafis Azhari dalam buku “Revolusi Dunia Pesantren”, bahwa anak ideologis mencerminkan akhlak dan karakteristik sesuai dengan misi dan ajaran Rasulullah, tanpa pandang bulu, apakah dia hanya sekadar teman, sahabat maupun murid yang menimba ajaran dari sang guru (mursyid). Sedangkan anak biologis, tidak jarang dihinggapi keangkuhan dan kesombongan, bahwa ia sudah menyandang identitas selaku keturunan dari seorang figur, yang seakan-akan dijamin kebaikan dan kesalehannya.
Oleh karena itu, kita menghormati orang tua, termasuk mertua, kakek-nenek, paman, bibi dan kakak, bukan lantaran kesamaan pandangan maupun ideologi, melainkan karena senioritas dalam ikatan darah. Jadi, antara menghormati orang dengan pandangan dan prinsip hidup adalah dua hal yang berbeda.
Dari perspektif lain, seringkali kita temukan para habaib yang memiliki kenikmatan dalam beribadah. Mereka terlihat begitu tenang dan khusyuk dalam menjalankan ubudiyah (zikir), meskipun belum tentu dia seorang ahli ilmu (fikr). Namun sejatinya, bila kita menemukan seorang intelektual dan pemikir, jika tak diimbangi dengan kemampuan berzikir biasanya dia akan menjauh dari jalan Tuhan (al-magdlub), tetapi sebaliknya seorang ahli zikir yang tak memiliki kualitas ilmu biasanya ia akan berada dalam kesesatan (al-dlallun). Jadi, antara zikir dan fikir harus selaras dan seimbang, tak terkecuali seorang habib. Tanpa menemukan titik keseimbangan antara keduanya, manusia cenderung bertindak berlebihan dan melampaui batas.

BACA JUGA: Kisah-kisah Karomah Kiai Banten
Jika kita menilik dari kacamata pemikiran Ali Zainal Abidin, yang juga ahli ilmu dan ahli ibadah, yang juga anak ideologis sekaligus anak biologis, nampaknya ikhtiar dan perjuangan agar kita konsisten di jalan kebaikan harus menjadi prioritas yang paling diutamakan. Meskipun perdebatan antara keduanya tak ubahnya suatu perdebatan antara tarik-menarik konsep jabariyah atau qadariyah, takdir atau ikhtiar, telur atau ayam. Apakah diperlukan tokoh antagonis untuk menunjukkan adanya protagonis dalam drama kehidupan yang disekenariokan Tuhan? Apakah memang diperlukan Firaun untuk menunjukkan kepahlawanan Musa, sebagaimana Muhammad yang meniscayakan adanya sosok Abu Lahab?
Tapi itu kan dulu, sebagai sejarah yang sudah terlewati. Masalahnya sekarang, kita mau menjadi sosok Musa ataukah Firaun? Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan diri kita di meja hijau mahkamah sejarah? Mau meneladani keangkuhan Abu Lahab ataukah kerendahan hati Nabi Muhammad? Meskipun, baik Abu Lahab maupun Muhammad sama-sama memiliki garis keturunan dari Abdul Muthallib dan Ibrahim juga?
“Tuhanku, jadikanlah semua keturunan kami sebagai orang-orang baik dan saleh,” demikian permintaan Ibrahim kepada Allah. Namun kemudian, Allah Sang Sutradara yang memiliki hak prerogatif menjawab, “Akan Aku kabulkan keinginanmu, wahai Ibrahim, kecuali bagi hamba-hamba-Ku yang tak mau berbuat baik.” []
*Pengasuh pondok pesantren Al-Bayan, Rangkasbitung, Banten Selatan.
Kirim tulisan Anda ke Islampos. Isi di luar tanggung jawab redaksi. Silakan kirim ke: islampos@gmail.com, dengan ketentuan tema Islami, pengetahuan umum, renungan dan gagasan atau ide, Times New Roman, 12 pt, maksimal 650 karakter.