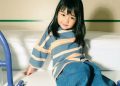Oleh: Enzen Okta Rifai, Lc.
Alumni perguruan tinggi International University of Africa, Sudan, menulis esai sastra di berbagai harian nasional luring dan daring.
enzenoktarifai@gmail.com
INDONESIA dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah perpustakaan terbesar kedua setelah India. Namun sayang, di era medsos ini jumlah perpustakaan yang berjibun itu sama sekali tak ada hubungannya dengan peningkatan minat baca orang Indonesia. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Syarif Bando selaku kepala perpustakaan nasional, Jakarta: “Jumlah perpustakaan kita cukup fantastis, sekitar 164.610 unit, sedangkan India memiliki hampir dua kali lipat dari Indonesia, sekitar 323.605 unit.”
Menurut Syarif Bando, selain minat baca yang sangat rendah, masyarakat kita masih menghadapi kendala yang lebih serius, yakni keterbatasan akses terhadap perpustakaan, juga kualitas buku-buku yang tidak memadai. Minimnya akses terhadap perpustakaan sangat terasa hingga ke tingkat desa dan kecamatan.
Dari total kebutuhan 7.094 perpustakaan kecamatan di seluruh Indonesia, baru terpenuhi 6 persen atau 600 perpustakaan yang letaknya hanya berpusat di wilayah Jawa. Konsekuensinya, akses masyarakat terhadap perpustakaan dan buku di luar Jawa masih sangat rendah.
BACA JUGA: Hukum Berdoa di Medsos
Ada perpustakaan dengan pelayanan dan kondisi sangat menarik serta membuat betah pengunjung. Namun, pada umumnya perpustakaan di tingkat desa punya kondisi yang sangat memprihatinkan, sehingga kurang menarik untuk dikunjungi, apalagi sampai berlama-lama membaca. Era digital juga menjadi salah satu kendala untuk menaikkan minat baca masyarakat. Terkait dengan ini, kita mengetahui data-data valid dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017), bahwa jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi internet mencapai 143 juta orang.

Mestinya, dengan terbukanya akses itu masyarakat lebih melek ilmu pengetahuan, literasi maupun kesusastraan, namun sayang kebanyakan masyarakat kita tidak mengakses sains, sastra, maupun ilmu-ilmu agama yang bersifat ilmiah dan layak dipertanggungjawabkan.
Banyak situs maupun web-web yang dapat mencerdaskan masyarakat seperti kompas.id, alif.id, islampos.com, nusantaranews.co, kabarmadura.id, litera.co.id, solopos.com, Jurnal Toddoppuli, termasuk jurnal-jurnal kampus. Tetapi, lagi-lagi sayang, masyarakat kita lebih suka mengakses medsos-medsos seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Mereka hanya sibuk mencari konten-konten menghibur, bukan mendidik. Bahkan, konten hoaks pun mereka sikat juga. Padahal, seumumnya masyarakat kita bisa menghabiskan waktu hingga 8 jam untuk berselancar di dunia maya.
Bangsa paling bawel
Tidak heran jika masyarakat Indonesia berada di urutan ke-5 sedunia sebagai netizen paling cerewet di media sosial. Laporan itu telah dirilis berdasarkan hasil riset Semiocast, lembaga independen terkenal di Paris. Dari hasil riset itu dapat dibuktikan, warga Jakarta tercatat sebagai masyarakat paling cerewet yang menuangkan segala amarah dan kejengkelannya melalui Twitter, bahkan lebih dari 10 juta tweet setiap hari. Bandung juga masuk dalam jajaran kota teraktif di Twitter di posisi ke-6.
Bisa dibayangkan, dengan ilmu yang sangat minim, malas baca buku, tetapi sangat suka menatap layar gawai berjam-jam, sibuk memgomentari ini-itu, tanpa melihat dan mempelajari latar belakang masalahnya. Karuan saja, jika kita membuka kembali novel Perasaan Orang Banten yang diadakan bedah bukunya untuk pertama kali (2012) di Rumah Dunia pimpinan Gol A Gong (Duta Baca Indonesia), kita akan mengenali sosok-sosok bawel dan ceriwis yang berkoar-koar tanpa didasari ilmu pengetahuan.
Tokoh-tokoh yang dinarasikan Hafis Azhari dalam novelnya itu, tak lebih dari pribadi-pribadi yang seakan memiliki DNA kaum inlander, banyak cocot tetapi miskin ilmu, yakni sosok-sosok manusia Indonesia yang gampang menjadi mangsa empuk para provokator, hoaks, adu domba dan fitnah-fitnah murahan.
Kecepatan jari untuk langsung like dan share melebihi kecepatan otak menimbang dan mencerna. Hal-hal ini – disadari atau tidak – telah menjadi masalah serius bagi negara kita untuk berkembang menjadi negara maju, karena bagaimanapun semua negara maju memiliki minat baca tinggi, melek literasi dan gemar kesusastraan.
Orang Jepang tak mau melewatkan waktunya tanpa membaca. Kita bisa dengan mudah menemukan orang Jepang membaca buku, koran, majalah di kereta api atau di taman-taman kota. Jikapun melihat gawai, kebanyakan mereka pintar mengakses ilmu pengetahuan. Hal yang sama juga terlihat di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat.
BACA JUGA: Perhatikan, 6 Hal yang Dilarang Diunggah di Medsos!
Kini, di berbagai negeri Afrika pun sudah mulai melek literasi. Pemenang nobel di bidang kesusastraan tahun 2021 (Abdulrazak Gurnah), membuat banyak generasi muda Tanzania menggelar forum-forum diskusi dan dialog tentang pentingnya dunia sastra bagi kemajuan peradaban bangsa.
Bagaimana Indonesia?
Secara global, UNESCO menempatkan posisi Indonesia di urutan kedua dari bawah terkait literasi. Data UNESCO menyebut, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya dari 1.000 orang Indonesia, cuma satu orang yang rajin membaca. Miris sekali, ternyata Indonesia berada di urutan ke-60 dari 61 negara soal minat baca.

Wilayah sastra, yang diidentikkan dengan literasi dan karya cipta penulisan juga sangat memprihatinkan. Produksi karya-karya sastra Indonesia, sejak tahun 2000 hingga dua dekade berikutnya, cukup marak di seluruh pelosok negeri. Namun, karena pengaruh dampak eforia dari kekuasaan militerisme selama tiga dekade sebelumnya, para penulis muda – yang terlahir pasca 1965 – memilih menerbitkan karya-karya mereka secara independen. Bahkan, di samping masih banyak yang terbit di pusat-pusat kota, semisal Jakarta, Yogyakarta dan Bandung, namun lebih banyak dari para penulis muda memilih menerbitkannya di kota-kota kecil di daerahnya, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
Kita ambil contoh dari karya sastra yang akhir-akhir ini banyak mendapat apresiasi publik, semisal novel Pikiran Orang Indonesia. Meskipun novel tersebut diterbitkan oleh penerbit independen, namun tetap sudah terdaftar dan ber-ISBN. Pemasarannya memang terbatas, hanya berpusat di toko-toko buku wilayah Banten dan sekitarnya. Namun, tidak sedikit penulis dan akademisi yang kemudian berbaik hati untuk menyebarluaskannya melalui jaringan internet (atas seizin penerbit dan penulisnya).
Penerbitan buku-buku sastra di daerah seumumnya terinspirasi dan digerakkan oleh komunitas sastra yang ada di setiap daerah, sehingga basis komunitasnya sangat beragam. Tentu saja perkembangan ini sangat positif, hingga perlu dicermati sebagai kajian historis kesusastraan Indonesia di era kekinian.
Terkait dengan kajian historis, maka adakah selama ini pengimbangan atau keselarasan antara perkembangan sastra (pasca Orde Baru) dengan munculnya penerbitan buku tentang sejarah sastra kita? Inilah yang menjadi ironi yang mengenaskan. Karena, lantaran stagnasi ini mengakibatkan buku-buku sastra Indonesia masakini menjadi kurang terlacak, kurang terdata, dan dengan sendirinya belum dikenal oleh pembaca luas, baik secara nasional maupun internasional.
Perkembangan sastra mutakhir Indonesia hendaknya tidak tercecer ke mana-mana, sehingga publik dapat mengakses dan mengenalinya satu persatu. Sejarah sastra tak lain merupakan bagian dari aspek pendidikan dan pembelajaran ilmu sastra juga. Tetapi, ketika ilmu pendidikan sastra tak didukung dengan pendokumentasian (yang meliputi pencatatan dan identifikasi) maka di manakah letak kepedulian bangsa terhadap dunia pendidikan sastra yang merupakan ujung-tombak kemajuan budaya dan peradaban?
Bagaimanapun, harus kita akui secara jujur bahwa kita memang belum mempunyai tradisi yang kuat dalam mendokumentasi karya-karya cipta di dunia literasi. Kita tidak menghendaki penerbitan sebesar Kompas dan Gramedia hanya berjibaku untuk kemajuan perusahaannya sendiri berikut cabang-cabangnya semata.
Di tingkat daerah, saat ini telah terjadi lonjakan perkembangan yang sangat pesat. Misalnya, di Jawa Timur, Madura, Batam, Sumatera hingga Banten, banyak sastrawan-sastrawan muda yang aktif menulis sastra, khususnya kumpulan cerpen dan puisi, baik dalam bentuk antologi banyak penulis maupun yang bersifat pribadi. Penulisnya memiliki keunikan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari kalangan jurnalis, mahasiswa, guru, dosen, pengasuh pesantren, ibu rumah tangga, hingga pekerjaan sederhana seperti tukang odong-odong yang menghibur anak-anak di jalanan.

BACA JUGA: Memberikan Nasihat Lewat Status di Medsos, Bolehkah?
Akan lebih optimal seandainya di tiap-tiap kabupaten atau provinsi ada penulis sejarah sastra yang berminat untuk menuliskan atau mendokumentasikan setiap karya sastra yang pernah ditulis di daerah masing-masing. Kemudian, hasilnya ditingkatkan dalam skala nasional. Dalam hal ini, institusi lembaga bahasa atau lembaga kesenian dan kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah, mesti memiliki kepekaan dan kepedulian.
Mereka memiliki segala perangkat dan fasilitas untuk melakukan pendataan dan pendokumentasian karya-karya sastra yang pernah diproduksi di setiap area wilayahnya. Dilengkapi dengan data-data yang tersedia di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dapat dijadikan sumber kelengkapan dokumen.
Bagaimanapun, materi sejarah sastra harus terus diperbaharui, sebagai gambaran tentang realitas produksi karya sastra di seluruh negeri hingga saat ini. Kita tak bisa hanya menggunakan buku sejarah lama, karena kita tak dapat memberikan gambaran sejarah sastra Indonesia pada perkembangannya yang mutakhir hingga saat ini. []