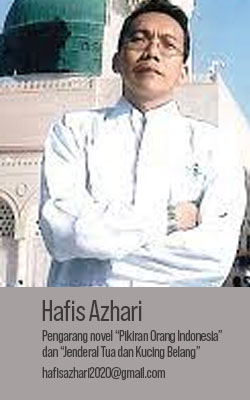 MEMAHAMI perselisihan antara Aisyah, istri Nabi Muhammad dengan menantu dan sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, tak bisa melalui tinjauan filosofis dan rasional tulen. Ia meliputi persoalan-persoalan internal rumah-tangga, penafsiran yang berbeda dalam pandangan agama, sekaligus memerlukan analisis dan tinjauan sufistik untuk mencermatinya.
MEMAHAMI perselisihan antara Aisyah, istri Nabi Muhammad dengan menantu dan sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, tak bisa melalui tinjauan filosofis dan rasional tulen. Ia meliputi persoalan-persoalan internal rumah-tangga, penafsiran yang berbeda dalam pandangan agama, sekaligus memerlukan analisis dan tinjauan sufistik untuk mencermatinya.
Perselisihan itu memang mengerucut pada pertempuran terbuka, yang kelak kemudian disebut “Perang Jamal”. Namun, bila dikaji dari kacamata orientalisme Barat, seakan-akan ia adalah peristiwa absurd, tak ubahnya dengan pertikaian keluarga-keluarga kerajaan di zaman pra Islam. Padahal, tak ada kejadian yang serba kebetulan dalam kehidupan ini. Semuanya sudah dirancang dalam kecermatan skenario Tuhan. Bahkan, sebagian dari peristiwa konflik dan peperangan di zaman sahabat hingga tabi’in, sudah diberitahukan oleh Nabi secara tersirat, tak terkecuali perbedaan pendapat antara mantan istri dan menantu Rasulullah tersebut.
Suatu hari, Rasulullah membisikkan sesuatu yang membuat Ali bin Abi Thalib merasa kaget, bahwa kelak di kemudian hari ia akan mendapat masalah dengan mantan istrinya Aisyah, setelah beliau wafat.
“Waduh, apakah itu artinya saya akan membahayakan keluarga Rasulullah?” tanya Saydina Ali.
“Tidak, tenang saja,” jawab Nabi, “nanti tempatkan saja Aisyah di tempat yang aman.”
Kata-kata bersayap dari pernyataan Rasulullah tak dipahami maksudnya, hingga Saydina Ali menengadah dengan tatapan berkaca-kaca. Apa yang dimaksud menempatkan Aisyah di tempat yang aman? Peristiwa apa gerangan yang akan ia alami dengan Aisyah, setelah Rasulullah tiada?
Meletusnya Perang Jamal
Banyak versi yang berpendapat mengenai penyebab terjadinya perang Jamal. Salah satunya adalah dendam Thalhah dan Zubair yang merasa punya hak untuk dipersamakan dengan Ali dalam hal kekuasaan. Di sisi lain, kepemimpinan Islam pasca wafatnya Rasulullah bukanlah semata-mata urusan pembagian kekuasaan, tapi amanat kekhalifahan yang harus diemban oleh figur yang mumpuni.
BACA JUGA: 4 Persoalan yang Dihadapi Khulafaur Rasyidin
Selain itu, Thalhah dan Zubair juga menuduh seakan-akan Ali adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas kematian Khalifah Utsman bn Affan. Karena diprovokasi oleh kedua aktor intelektual itu, mantan istri Nabi, Aisyah, menjadi korban dari propaganda mereka. Di sisi lain, Aisyah sendiri tak punya kepentingan apa-apa untuk menuntut balas dendam atas kematian Khalifah. Lagipula, dia sendiri belum tahu buktinya, jikalau Ali diisukan telah berbuat senekat itu.
Sementara itu, kaum Mu’tazilah berpendapat bahwa rumor yang merebak seakan-akan Ali haus kekuasaan, maka Aisyah merasa perlu mendukung pergerakan untuk menjatuhkan kepemimpinan Ali. Padahal, Ali sendiri tak menghendaki kekhalifahan berada di tangannya. Ia menjadi pemimpin karena desakan masyarakat Madinah (baik Muhajirin maupun Anshar), yang kemudian terpaksa ia menjalankannya sejak 655 Masehi (35 Hijriyah). Sedangkan, Thalhah dan Zubair memang masih awam dalam memahami amanat kekhalifahan, yang dikiranya semacam bagi-bagi kue kekuasaan agar dapat menikmatinya.
Kedua orang itu kemudian menuntut Ali melepaskan kewenangannya agar wilayah Bashrah, Kufah, Irak hingga Yaman berada di bawah kekuasaan mereka. Menurut Ali, keduanya tak memiliki kapasitas untuk memimpin, karena kepemimpinan Islam tak layak diminta-minta sebagaimana pengemis yang menadahkan kedua tangannya. Thalhah dan Zubair terus melakukan manuver-manuver politik di sekitar Mekah, meski keberangkatannya dari Madinah menuju Mekah dengan alasan “umroh”. Rupanya, sesampainya di Mekah, mereka berjumpa dengan Aisyah lalu mengompori mantan istri Nabi itu untuk melakukan pemberontakan, oleh karena tuduhan bahwa kematian Khalifah Utsman akibat pembunuhan yang dilakukan orang-orang terdekat Ali.
Tulisan Saydina Ali dalam “Nahjul Balaghah” bukannya tanpa dasar dan pembuktian yang akurat. Ia telah mengumpulkan berbagai data dan bukti perihal beberapa sahabat Nabi yang tergoda oleh ambisi dan hasrat kekuasaan duniawi. Misalnya dalam khotbah 172 dinyatakan: “Thalhah dan Zubair telah memprovokasi Aisyah, serta menyeretnya bagaikan budak belian.”

Menurut Saydina Ali, gerakan separatisme (makar) dari Thalhah dan Zubair kurang mendapat simpati publik manakala mereka tak melibatkan mantan istri Rasulullah yang dianggap punya otoritas. Bahkan, untuk mempersiapkan pasukan pun mereka membutuhkan restu dari Aisyah. Abdullah bin Ammar dan Ya’li bin Umayyah dari Yaman juga mempersiapkan sekitar 600 onta dan uang 1000 dinar, yang kemudian perkumpulan pasukan segera dilaksanakan di depan rumah Aisyah. Pada akhirnya, pasukan dengan jumlah 3000 orang siap bergerak, di mana 900 dari jumlah itu adalah penduduk Mekah dan Madinah yang menentang kepemimpinan Ali.
Ketika pasukan sampai di sumber mata air Hau’ab, Aisyah mendengar suara lolongan anjing, sehingga ia memiliki firasat kurang baik dan hendak kembali ke rumahnya. Aisyah memang pernah mendengar kata-kata bersayap yang diperingatkan Rasulullah, agar dirinya berhati-hati jika mendengar lolongan anjing di sekitar Hau’ab. “Ada apa dengan kalian? Berhati-hatilah dengan suara lolongan anjing di sekitar Hau’ab,” demikian firasat Nabi yang disampaikan pada Aisyah, ketika beliau masih hidup.
Namun, Thalhah dan Zubair berkilah bahwa itu bukanlah lolongan anjing, dan nama mata air itu bukanlah Hau’ab. Pasukan terus melaju hingga mencapai Bashrah. Seketika itu, Khalifah Ali mengutus salah seorang jenderalnya, Utsman bin Hunaif yang bertugas di Bashrah, agar memerintahkan Imran bin Husain dan Abu Aswad al-Duali untuk segera menemui Aisyah, serta menanyakan apa yang menjadi motif dari pemberontakannya pada pemerintahan Ali.
Lalu, Aisyah berkata dengan lantang, “Orang-orang jahat telah menyerang Madinah dan Khalifah Utsman terbunuh secara sadis, hartanya dijarah, kehormatan tanah harem dinodai, dan bulan-bulan suci telah dilanggar.”
Khalifah Ali kemudian menjelaskan, bahwa dirinya telah mengupayakan perdamaian seoptimal mungkin di kalangan kaum muslimin yang berselisih. Ia menyarankan agar Aisyah taat pada perintah Allah dan Rasulullah, dan segera pulang ke rumah sebagaimana ketaatan istri-istri Nabi lainnya.
Imam Ali tak diindahkan
Ketika beberapa kabilah menyatakan dukungannya kepada pasukan Aisyah, kemudian sekitar 1.000 onta dikirim dari Yaman untuk menentang pemerintahan Ali, maka pasukan itu bergerak ke arah Bashrah. Aisyah sendiri menaiki onta betina berambut merah, dilengkapi dengan baju besi, yang kemudian diberi nama “Askar”. Perang ini kemudian dinamakan Perang Jamal, karena banyaknya pasukan Aisyah yang mengendarai onta yang telah disumbangkan penduduk Yaman.
Pada mulanya Khalifah Ali enggan bertempur dengan pasukan, di mana salah seorang mantan istri Rasulullah terlibat sebagai musuhnya. Ia berkali-kali memerintahkan mereka agar mundur dan pulang ke kampung halamannya. Namun, Thalhah mendesak para pasukan agar terus merangsek, dengan alasan mereka harus membalas-dendam atas kematian Khalifah Utsman bin Affan.
Ketika diperingatkan tentang wasiat Nabi perihal perang saudara ini, Zubair memutuskan undur-diri, namun kemudian didesak oleh anaknya (Abdullah bin Zubair), bahwa bendera yang sudah dipancangkan membuat ia pantang untuk mengalah dan mundur ke belakang. Padahal sejatinya, suatu keraguan dalam memutuskan tindakan fatal, bahkan mengalah sekalipun bisa dibenarkan demi kokohnya persatuan dan kemaslahatan bersama.

Tak lama kemudian, pasukan Thalhah menghujani pasukan Ali dengan anak-anak panah, sampai kemudian kedua pasukan itu menabuh genderang “perang” dan terjadilah pertempuran terbuka yang tak bisa dihindarkan lagi. Sayap sebelah kanan pasukan Ali dipimpin oleh Malik al-Asytar, dan sayap sebelah kiri oleh Ammar bin Yasir, sedangkan bendera pasukan dipegang oleh Muhammad bin Hanafiyah. Pada pertempuran ini, Hasan bin Ali berada di sebelah sayap kiri, dan Husain bin Ali berada di sebelah sayap kanan.
Mengingat firasat Nabi
Terbunuhnya Thalhah dan Abdullah bin Zubair, membuat pasukan yang dipimpin Aisyah menjadi kocar-kacir. Sementara, Ali memerintahkan untuk memenggal kaki Askar hingga Aisyah pun tersungkur ke tanah. Pasukan Ali berhasil menawan Aisyah bersama ratusan tawanan perang lainnya. Kemudian, atas perintah Khalifah Ali, Aisyah pun segera diamankan, jangan sampai terluka, juga jangan sampai ada perampasan harta benda.
BACA JUGA: Siapa Habib Umar bin Hafidz, Ulama dari Yaman?
Ibnu Abbas kemudian diperintahkan agar menemui dan menasehati Aisyah, sampai kemudian Aisyah benar-benar menyesal, serta menyadari kekhilafan yang diperbuatnya, hingga menimbulkan ratusan korban di kalangan kaum muslimin. Dalam beberapa riwayat, tiapkali mengenang peristiwa itu, Aisyah menangis sesenggukan karena suatu penyesalan, hingga air matanya membasahi kerudungnya.
Saydina Ali setback ke masa lalu, mengingat ketika Rasulullah menyampaikan pesan tersirat semasa hidupnya, bahwa ia akan menghadapi problem dengan Aisyah di masa yang akan datang.
Saat itu, Ali merasa kaget, dikhawatirkan ia akan melukai salah seorang istri Rasulullah, setelah ditinggal wafat oleh beliau.
“Tenang saja,” jawab Nabi, “nanti tempatkan saja Aisyah di tempat yang aman.”
Kata-kata bersayap dari pernyataan Rasulullah itu, kini telah dipahami maksudnya. Seketika itu, Saydina Ali segera memerintahkan kaki-tangannya agar segera mengamankan Aisyah, serta memulangkannya secara terhormat ke rumahnya di kota Madinah. []
Kirim tulisan Anda ke Islampos. Isi di luar tanggung jawab redaksi. Silakan kirim ke: islampos@gmail.com, dengan ketentuan tema Islami, pengetahuan umum, renungan dan gagasan atau ide, Times New Roman, 12 pt, maksimal 650 karakter.















