POLIGAMI, atau istilah yang lebih presisi, poligini, dalam bahasa Indonesia (silakan merujuk ke KBBI) menunjuk pada sistem perkawinan yang membolehkan seorang suami memiliki beberapa istri dalam waktu bersamaan. Dalam bahasa, tidak ada batasan jumlah istri yang dimiliki. Tapi secara syariat, ia dibatasi maksimal empat orang istri.
Fakta poligami di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabat radhiyallahu ‘anhum ajma’in memang lebih ke pembatasan. Sebagian shahabat memiliki istri yang sangat banyak, sesuai dengan tradisi mereka di masa itu, kemudian Nabi memerintahkannya untuk menceraikan sebagian istri dan mempertahankan 4 saja di antara istri-istri tersebut.

Ini misalnya terjadi pada Ghaylan bin Salamah Ats-Tsaqafi, yang saat masuk Islam, punya 10 istri. Nabi kemudian memerintahkannya mempertahankan 4 orang dan menceraikan sisanya.
BACA JUGA: Berpoligami, Antara Keadilan dan Kezaliman
Namun fakta ini, tidak berisi taqyid (pembatasan hukum), bahwa berpoligami yang diizinkan hanya pada kasus orang yang beristri lebih dari 4, kemudian disuruh membatasi hanya pada 4. Beristri lebih dari satu tetap dibolehkan (masyru’), pada laki-laki yang awalnya punya satu istri, kemudian ingin menambahnya.
Yang diperselisihkan ulama, hanya pada, mana yang lebih utama, beristri lebih dari satu atau hanya beristri satu. Kalau dua hal diperselisihkan keutamaannya, berarti dua-duanya hal yang boleh dilakukan.
Seperti perselisihan, mana yang lebih utama saat safar, meringkas shalat (qashar) atau menyempurnakannya (itmam), itu diperselisihkan karena keduanya sama-sama boleh dilakukan.
Jadi membuat narasi, seakan beristri lebih dari satu bukan sesuatu yang masyru’, hanya karena monogami dianggap lebih utama, adalah narasi yang tidak tepat, cenderung menyembunyikan hal yang tak layak disembunyikan.
Syafi’iyyah dan Hanabilah dengan tegas menyatakan, monogami lebih utama dari poligami, kecuali jika ada hajat yang jelas pada laki-laki untuk poligami. Dalam Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (41/220) disebutkan:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة.
Artinya: “Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat, dianjurkan bagi laki-laki tidak menikah dengan lebih dari satu istri, tanpa ada hajat yang jelas.”
Poligami atau Monogami?

Namun ingat, ini soal keutamaan (afdhaliyyah), bukan soal boleh tidaknya (masyru’iyyah). Menarasikan afdhaliyyah dan masyru’iyyah harus jelas bedanya.
Apalagi di zaman fitnah sekarang, saat banyak orang lebih bisa menerima perzinaan yang dilakukan suka sama suka (konsensual seks) dibandingkan berpoligami yang jelas dibolehkan dalam Islam. Jangan pernah mau menjadi bidak catur untuk menyerang ajaran Islam.
Poligami hukum asalnya mubah, namun hukumnya bisa berubah menjadi sunnah (mustahab), makruh, bahkan haram, sesuai keadaan si pelaku.
Jika memang ada laki-laki yang kaya, penghasilan stabil, punya jiwa kepemimpinan yang baik, shalih dan bisa berlaku adil dalam nafkah zhahir dan giliran bermalam, sedangkan ia khawatir jatuh pada perzinaan atau perselingkuhan jika tidak menambah istri, maka beristri lebih dari satu adalah solusi untuknya, dan ia dianjurkan (disunnahkan) untuk melakukan hal tersebut.
BACA JUGA: Mengapa Rasul Berpoligami?
Poligami atau Monogami?
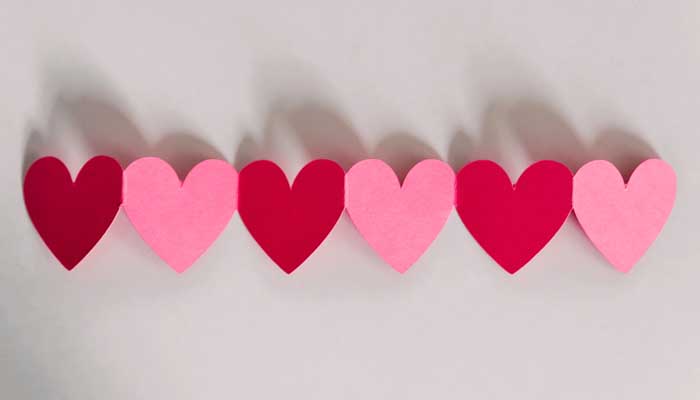
Sebaliknya, orang yang miskin, penghasilan tak menentu, memberi nafkah satu keluarga (istri dan anak) saja masih kesulitan, maka ia tidak dianjurkan beristri lebih dari satu. Hukumnya makruh untuknya.
Bahkan jika jelas menimbulkan dharar bagi istri-istrinya, dan ia tidak mampu berbuat adil dalam nafkah dan giliran bermalam, maka haram untuknya beristri lebih dari satu.
Sikap dan narasi yang perlu kita tunjukkan terkait beristri lebih dari satu ini ada dua: (a) Menjelaskan hukum berpoligami secara proporsional, sebagaimana biasanya para ulama fiqih menjelaskan, (b) Menjelaskan masyru’iyyah-nya berpoligami beserta hikmahnya, sebagai bantahan kepada pihak-pihak yang terpengaruh ide-ide Barat, feminisme dan lainnya, yang menganggap berpoligami sebagai kejahatan dan keterbelakangan. Wallahu a’lam. []
Facebook: Muhammad Abduh Negara















