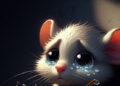Oleh: Dzikri Asykarullah
SEPERTI biasa, setiap akhir pekan aku beristirahat sejenak dari rutinitas mengurus usaha atau lembar lembar pekerjaan kantor yg seolah tak ada habisnya.
Menghabiskan waktu di toko buku atau mencari destinasi wisata baru, sendirian. ya sendirian, bukan karena tak banyak kawan tapi aku memang tidak terlalu menyukai keramaian.
Ketika langit mulai menampakan semburat jingga, dan adzan maghrib berkumandang itu adalah waktuku pulang, dan aku akan segera mencari masjid untuk sembahyang. bukan masjid kampus atau masjid yg biasa aku kunjungi, tapi aku akan mencari masjid di tengah kampung, di seberang jalan, dimanapun masjid yg belum pernah aku kunjungi sebelumnya.
Sore ini masjid di seberang Jalan Kaliurang, tak jauh dari kampus UII adalah ruang temu selanjutnya. masjid yang hampir separuh jama’ahnya adalah para penyandang difabel.
Baru saja mulai mengambil air wudhu aku sudah merasa kasihan, bukan kasihan kepada mereka yg wudhu sembari berpegangan ke dinding karena kaki palsu mereka lepas terlebih dahulu sebelum wudhu, tapi aku kasihan terhadap diriku sendiri, apakah aku masih pantas, betapa nanti syurga akan penuh dengan orang-orang ini, orang-orang yang tetap menyembah Allah dengen sepenuh hati, tanpa mengutuk takdir yang Allah berikan kepada mereka.
Selepas salam setiap menyempatkan diri sholat disini, air mataku selalu menetes karena Allah seolah sedang menasihatiku dengan lembut bahwa seberat apapun masalah hidup yang kita hadapi, sama sekali kita tidak pantas untuk mengeluh dan menyalahkan takdir. []